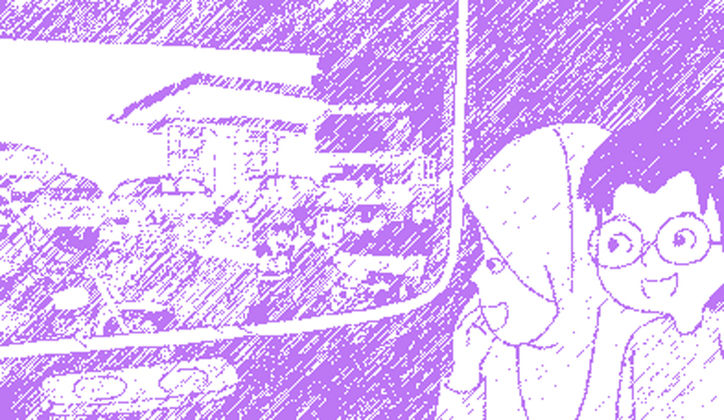BUS lintas Sumatra menembus dingin pagi. Pelabuhan penyeberangan feri Bakauheni-Merak sudah dilewati seperempat jam yang lalu. Kini bus eksekutif yang kutumpangi meluncur menuju Jakarta. Dua malam berada di bus membuat badanku pegal-pegal. Ingin rasanya kurebahkan punggungku lurus di kasur nyaman. Kusenggol suamiku yang sesekali menutup mulut karena menguap menahan kantuk.
“Sudah masuk Cilegon,” jelasnya padaku. Matanya menyapu pandangan ke jendela di sampingku.
“Hmm, lumayan. Masih jauh lagi…,” bujukku menenangkan diriku sendiri. Kurapatkan jaket hitam menepis dingin AC bus.
Hari ini aku pulang kampung. Lebih tepatnya mungkin pulang kota. Pulang ke kota kelahiranku, Jakarta, setelah hampir setahun merantau di luar Jawa. Lagu Aryati, ciptaan Ismail Marzuki menggelitik di telingaku. Lagu lawas yang pernah dinyanyikan Kris Biantoro disetel berulang di bus ini. Membuatku hanyut dalam kenangan masa kecil bersama ibuku. Dulu ibuku suka bersenandung lagu itu. Aryati, judul lagu yang mirip dengan nama ibuku. Ah,sungguh kerinduanku padanya telah membawaku ada di bus ini sekarang. Tembang lagu itu kembali menghangati suasana bus ini.
Aryati…Dikau mawar asuhan rembulan
Aryati…Dikau gemilang seni pujaanpujaan
Dosakah hamba mimpi berkasih dengan tuan
Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam
Dosakah hamba memuja dikau dalam mimpi
Hanya dalam mimpi
Aryati
Dikau mawar di taman khayalku
Tak mungkin dikau terpetik daku
Walaupun demikian nasibku
Namun aku bahagia seribu satu malam..
Lagu itu mengajakku masuk dalam pusaran kenangan masa kecilku bersama ibuku…
“Alya, ayo bawa kardusnya ke sini..!.Susun gombal perca di dalamnya. Pussy gak lama lagi lahiran ini,” seru ibu sambil bercanda dengan Pussy, kucing peliharaan di rumah kami.
Kudekati Pussy, dan kuelus lembut kepala kucing belang putih, coklat kekuningan. Ekornya kini bergerak-gerak tanda senang. Saat itu usiaku sepuluh tahun. Bermain bersama Pussy sepulang sekolah ternyata mengasyikkan. Sesekali Pussy bermanja, dan menarik perhatianku dengan berguling-guling di lantai.
Ibuku memang penyayang kucing. Terbayang foto ibu semasa gadis dengan rambut panjang dikepang dua sedang tersenyum menggendong kucing,
“Duh kenapa semakin dewasa, aku malah geli dengan bulu-bulu kucing…? Apalagi kalau ada kucing yang dekat-dekat kakiku, reflek kuangkat kakiku menghindar darinya,” gelitik hatiku heran.
Membuka kenangan masa kecilku bersama ibu tersayang, ada episose yang kerap menyisakan penyesalan di diriku. Aku kecil, adalah seorang anak yang keras kepala, dan kurang sabar. Semua keinginanku maunya segera terpenuhi, dan terlaksana dengan cepat. Jika ada sesuatu yang tak berkenan di hatiku,, maka orang serumah akan menyaksikan kemarahanku yang meledak di hari itu. Dan apa yang kuperbuat?.
‘Treet.. treet…treet..”
Seluruh kain gorden pintu kamar yang terpasang rapi, terlepas karena kutarik paksa. Habis..!, dan selalu menjadi sasaran kekesalanku. Dulu, model gorden pintu, atas kainnya dipasang pengait yang bisa lepas jika ditarik kuat-kuat.
Ajaibnya ibu diam saja tidak bereaksi, jika aku sedang kesal. Cuma memandangku sambal duduk. Tak ada umpatan kemarahan sedikit pun keluar dari mulutnya.
Dibiarkan saja hingga aku puas menarik ketiga gorden, penutup pintu kamar di ruang tengah, lantai bawah rumahku. Setelah selesai, biasanya aku lebih tenang,.
Terlampiaskan sudah kemarahanku saat itu. Tinggal ibuku nanti merapikannya. Memasang kembali gorden yang berserakan di lantai karena kutinggalkan begitu saja.
Itulah ibuku yang baik dan penyabar. Kakaku, mbak Ris pernah cerita padaku,
“Alya.. tau gak kamu ?. Kalo ibu kita tuh.., baik banget sama kita Teman-teman Mbak Ris cerita, kalo tangan ibu mereka sering lincah mendarat di tubuh mereka. Ada teman Mbak Ris yang pahanya memerah bekas cubitan, membiru kena pukulan atau jeweran mampir di telinga mereka. Pokoknya ngeri mbak dengarnya…” Bertubi-tubi mbak Ris cerita tentang ibu teman sekelasnya.
“Alya…,” lanjut Mbak Ris memangilku sambal tersenyum.
Ibu kita boro-boro mau nyubit, mukul, atau jewer telinga kita, bersuara keras saja hamper tidak pernah kita dengar ya ?…”
Aku tertunduk tersadar, membenarkan seratus persen ucapan mbak Ris
“Ya betul, Mbak Ris. Ibu kita sangat baik, dan sabar,“ kataku menambahkan.
Bapakku menjabat posisi penting di pemerintahan, sehingga dulu hidup kami sekeluarga berkecukupan. Tapi tetap saja sikap ibu bersahaja, meskipun ada asisten rumah tangga yang membantu keluarga kami. Di pagi hari, ibu menyiapkan bekal sekolah dan menemani anak-anaknya makan. Tak jarang aku dan kakakku asyik membaca buku setiba pulang sekolah,sehingga lalai makan siang.
“Ayo makan ini dulu, Alya,” kata ibu sambal menyuapiku sesendok nasi hangat, sop dan cincang goreng kering daging sapi. Menu favoritku ini, sebentar sudah terlahap masuk mulut.
Hidup ibuku berisi kedermawanan dan limpahan maaf untuk orang-orang sekitar. Bahkan seingatku, dulu banyak sanak saudara, dan kerabat ibu, ikut tinggal menumpang di rumah kenanganku. Aku jadi ingat Parmi, anak sebayaku yang ikut membantu di rumahku. Karena cemburu pada ibu yang sangat baik padanya, membuat sikapku ketus kepada Parmi. Ibu menasihatiku, tapi aku malah merasa ibu membelanya.
“Oh…, alangkah buruknya perangaiku semasa kecil..”. Kuhela napas penjang, menyesali masa kecilku.
Kaca jendela di samping kiriku mulai menghangat. Bus yang kutumpangi berjalan melambat melewati kawasan industri. Truk-truk besar ramai lalu lalang sepanjang jalan ini. Sambil meneguk minuman, kusodorkan roti isi coklat ke suamiku. Dengan mata setengah terpejam, disobeknya potongan roti masuk mulutnya, sekedar membuang rasa kantuk dan lapar. Perjalanan darat lintas Sumatra menuju Jakarta di tahun 90-an cukup melelahkan fisik kami berdua.
“Masih satu jam lagi kita baru sampai, Sayang..”, ucap suamiku pelan sambil menutup mata, dan tidur lagi.
Lagu Aryati, kembali mengalun bersama kenangan ibuku yang berputar lagi di memoriku…
Setelah makan malam, dan mengerjakan PR sekolah, biasanya aku dan mbak Ris datang ke kamar ibu. Bersama Gung, dan Yudi adik lelakiku, kami kumpul dan bersenda gurau di dekat ibu yang berbaring di kasur besar. Kuambil posisi tidur sebelah kiri ibu, dan ketiga saudaraku mengambil posisi tidur senyamannya.
“Tidak.., kami belum mau tidur.” Ini adalah momen istimewa yang menyenangkan bagi kami, anak-anak ibu. Waktunya mendengar cerita seru ibuku. Aku bangga pada ibuku. Ibu dulu pegawai negeri di perpustakaan, dan hobi membaca buku. Namun setelah anak pertama lahir, ibu berhenti bekerja dan memilih menjadi ibu rumah tangga.
Dari tujuh anak ibu, tinggal kami berempat yang masih suka mendengar dongeng ibu sebelum tidur. Tiga kakakku telah beranjak besar dan disibukan urusan yang lain. Cerita legenda mulai dari Timun Emas, Bawang Merah Bawang Puth, Rawa Pening, Dewi Sri, Lutung Kasarung, Sangkuriang, Roro Jonggrang dan lainnya, pertama kali justru kudengar dari ibuku, sebelum akhirnya membaca kembali dongeng legenda itu di buku-buku. Puas dengan cerita rakyat, biasanya ibuku menyelipkan kisah pengalaman masa kecilnya hingga dewasa.
Ibuku perempuan yang cerdas. Menanamkan akhlak terpuji dengan media yang menyenangkan, lewat cerita pengantar tidur yang dirindukan anak-anaknya. Teringat kisah ibu sewaktu muda, galau karena harapannya tidak tercapai, maka kerjanya sehari-hari hanya tidur dan bermalas-malasan. Ibu bercerita, tiba-tiba nenek yang sudah meninggal datang dalam mimpi ibu, dan berpesan kepadanya,
“Orang hidup tidak boleh tidur saja. Orang yang sudah mati kalau masih bisa, pada mau bangun…”
Terbangun dari mimpi itu, kata ibuku, ia bergegas mengerjakan apa yang bisa dilakukannya. Mencuci seprei, bersih-bersih rumah, ikut kursus menjahit, menulis puisi, dan aktivitas bermanfaat lainnya. Mumpung masih ada kesempatan hidup dan beramal di dunia, katanya.
Semua cerita ibuku menakjubkan. Namun ada kisah paling seru menurutku, yaitu cerita kelahiranku. Melahirkan aku si bayi sungsang, sampai-sampai persalinan ibu harus dibantu oleh lima orang perawat. Hidupnya dipertaruhkan demi keselamatanku. Tanda kasih sayang ibuku bahkan terus membekas. Ibu tunjuk gigi depan atasnya yang lebih menjorok ke depan, dan berkata, “ini perjuangan Ibu menahan sakit, agar Alya selamat,” ujarnya memelukku erat.
Perjalanan hidup manusia selalu ada suka dan duka. Ada tawa, dan tangis. Suratan takdir pun membawa kondisi ekonomi keluargaku berubah. Bapakku wafat di usia empat puluh enam tahun, saat aku kelas dua SMP. Karir bapak di pekerjaannya tengah menaiki puncak kecemerlangan. Setelah empat puluh hari dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo karena sakit liver, para dokter angkat tangan, dan beberapa hari dirawat di rumah, akhirnya bapak wafat.
Ibu terpaksa menjual banyak aset peninggalan bapak. Bersyukur bapak mewarisi banyak peninggalan harta berupa tanah. Semua itulah yang ibu kelola untuk membayar keperluan sekolah anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari. Perjuangan ibuku tak kenal lelah. Satu-satu anak ibu, akhirnya tamat kuliahnya di Perguruan Tinggi.
“Ibu sudah bekali anak-anak ibu dengan ilmu, bukan harta. Manfaatkan. ilmumu sebaik-baikya. Jika bekalmu harta,maka ketahuilah bahwa suatu hari itu akan habis.. Tapi bekalan ilmu akan menjaga pemiliknya dari kehinaan meminta-minta.”
Kusibak gorden jendela di samping kiriku. Bus yang kutumpangi sudah masuk Kalideres, dan beberapa penumpang bersiap-siap turun di terminalnya. Jaket hitam kubuka. Dingin AC bus mulai berkurang. Suamiku terjaga dan merapikan rambut ikalnya, lalu tersenyum menatapku.
“Sabar ya, masih beberapa terminal sebelum sampai ke rumah ibu..’. Kusandarkan kepalaku di bahunya. Perlahan mataku memberat. Setengah terjaga muncul bayangan ibu bersama tmbang lawas yang mengalun syahdu memenuhi ruang bus.
Saat itu senja terakhir di bulan Syaban beberapa tahun yang lalu. Semburat jingga kanvas langit perlahan memudar, dan burung-burung terbang kembali ke tempat semula. Kulihat ibuku lekat memandang sebuah buku kecil, berwarna coklat. Jari telunjuknya menyeka tetes air bening di ujung matanya. Direngkuhnya bahuku mendekati dirinya,
“Di buku ini Alya, tercatat segala pinta istimewa Ibu kepada Allah,“ bisik Ibu membuka lembaran tengah buku kecil itu. Sembari memperbaiki letak kacamata, jemari tuanya menunjuk sebaris kalimat singkat,
“Semoga anakku menyelesaikan kuliahnya, dan bisa wisuda”. Tertera jelas nama mbak Ris terselip di baris doa itu. Bibir ibuku bergetar bahagia. Wajahnya berseri menatapku.
“Bukankah doa ini sudah terkabul ? “. Ibuku tersenyum manis. Ditandainya kalimat akhir dalam buku kecil itu dengan tulisan, Alhamdulillah. Buku itu digesernya, persis di hadapanku. Jemari telunjuknya menandai, sederet kalimat di bawahnya.
“Lihat Alya, bukankah kalimat yang Ibu tulis di Ramadan tahun lalu, kini menjadi nyata?.” Takjub, kutatap wajah sumringah ibuku. Jemari tuanya khusyuk menuliskan kembali baris-baris harapan dalam buku kecilnya. Bertepatan adzan maghrib yang berkumandang di ujung Syaban, beberapa tahun yang lalu.
“Ibu…oh ibu…. Namamu kueja dengan segala rasa sayang,” bisik hatiku
Bibirku merekah mengingat kenangan itu. Meskipun dulu aku tak bertanya lebih jauh kepadanya, doa-doa apa saja yang pernah tersemat untukku. Namun kuyakin, keberkahan dalam hidupku adalah bagian untaian doa-doa ibuku yang terpinta. Pun di saat istimewa terkabulnya doa di sepanjang tahun kehidupan ibuku, bulan Ramadan.
Pelukan suamiku di pinggangku, mengakhiri kenanganku sepanjang jalan tadi bersama ibuku tersayang.
“Kita sudah sampai, Sayang. Ayo siap-siap..,” ajaknya menarik tanganku meninggalkan bus itu. Sayup-sayup lagu Aryati kembali memenuhi ruang hatiku.
“Ibu aku rindu..”. ***
————————–
 Asih Drajad Lumintu, tinggal di Pekanbaru. Perempuan berlatar Pendidikan Bahasa Arab IKIP Jakarta dan Pendidikan Islam UIN Suska Riau ini, mulai menekuni dunia tulis menulis belakangan ini. Menggagas Kelas Perempuan Menulis di Komunitas Ceria (Cita Perempuan Indonesia) secara online. Kreasi tulisannya bisa dilihat di : https://instagram.com/komunitasceria. *
Asih Drajad Lumintu, tinggal di Pekanbaru. Perempuan berlatar Pendidikan Bahasa Arab IKIP Jakarta dan Pendidikan Islam UIN Suska Riau ini, mulai menekuni dunia tulis menulis belakangan ini. Menggagas Kelas Perempuan Menulis di Komunitas Ceria (Cita Perempuan Indonesia) secara online. Kreasi tulisannya bisa dilihat di : https://instagram.com/komunitasceria. *
Baca: Cerpen Gandi Sugandi: Puasa Tanpa Kepala Keluarga